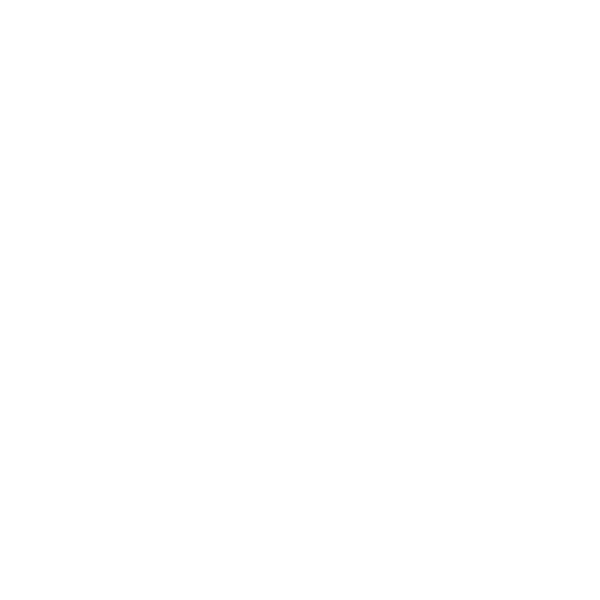Perkembangan pesatnya bahasa asing menjadi keniscayaan di era borderless saat ini. Pergaulan internasional membuka keran-keran kesempatan ber-relasinya warga dunia dalam peran-peran multidimensional di berbagai bidang. Bahasa tidak lagi tunduk pada kepemilikan lokal, melainkan peran fungsionalnya sebagai pemersatu manusia dari segala penjuru. Memotret fenomena ini sebagai salah satu ujian ketahanan bahasa Indonesia menjadi menarik. Mengingat Bahasa Indonesia merupakan salah satu bahasa dengan penutur terbanyak di dunia.

Masalah yang penting untuk ditelaah kemudian adalah pada penempatan bahasa Indonesia sebagai warisan perjuangan bangsa yang kian tidak mendapat tempat dihati para agent kulturnya. Penggunaan Bahasa Indonesia tidak lagi mendominasi ruang-ruang publik dalam setiap aktivitas kehidupan warganya. Fenomena diglossia terjadi ketika terdapat bahasa yang diposisikan pada tempat yang rendah, sementara bahasa lainya pada tempat yang lebih tinggi dan dinilai lebih prestige. ‘Peperangan’ ini tidak dapat dihindarkan dengan hadirnya bahasa asing yang kian menjamur di Negara dengan pluralitas bahasa dan budaya ini.
Oleh karenanya menjadi penting jika kesadaran akan permasalahan ini direspon dengan baik oleh dunia pendidikan. Mengingat salah satu domain yang efektif dalam upaya pemertahanan bahasa Indonesia adalah melalui aktivitas pendidikan, baik formal, informal maupun non formal. Wardhaugh (2006) dalam bukunya berjudul An Introduction to Sociolinguistics mendeskripsikan bahwa kemauan menggunakan bahasa tertentu pada wilayah pendidikan dapat memperpanjang ‘kehidupan’ bahasa tersebut.
Jika kita kaitkan dengan kondisi faktual pendidikan nasional, permasalahan bahasa tentu terkandung di dalam konten kurikulum maupun arah kebijakan lembaga pendidikan yang cenderung Internationally Based Oriented. Misalnya Bahasa Inggris, Arab, Perancis, Mandarin mendapatkan keistimewaan dengan beragam program intensif dan peminatan. Selain memang beberapa diantaranya menjadi mata pelajaran wajib. Tentu kontradiktif jika kita menyaksikan bahwa ternyata bahasa Indonesia tidak mendapatkan previlage seperti bahasa asing, sehingga jarang diminati oleh peserta belajar. Oleh karenanya urgen untuk memberikan penilaian bahwa sejauh mana bangsa ini berupaya merespon globalisasi, dengan tidak mengabaikan lokalitas tradisi sebagai jati diri dan karakter bangsa Indonesia. Salah satu aset bangsa yang dapat diselamatkan adalah generasi muda disemua jenjang pendidikan sebagai subjek dan objek dalam menerima pembelajaran bahasa-bahasa asing disekolah.
Mur dan Olga (1998:5) menguraikan secara baik tentang kecerdasan anak dan keistimewaanya dalam mempelajari bahasa. Anak secara lahiriah memiliki kemampuan untuk menguasai lebih dari satu bahasa, dari bahasa ibunya (mother tongue) hingga bahasa asing. Hal tersebut dilakukan dengan insting dan keahlianya dalam masa usia emas (golden age) untuk mudah merespon dan mengkaji sesuatu yang baru. Digambarkan bahwa anak memiliki kecenderungan untuk menyukai aktivitas percakapan, menangkap pesan atau maksud, kemampuan imajinatif yang baik, dan kemampuan untuk belajar secara mandiri. Karena pada hakikatnya setiap anak memiliki keragaman kecerdasan seperti diungkapkan oleh Gardner (1991), diantaranya matematis-logis, verbal, musikal, kinestetik, intrapersonal, interpersonal dan kecerdasan visual. Oleh karenanya menjadi bijak jika anak diposisikan dalam ke-khas-an sebagai prbadi dengan multiple-intelegence.
Kaitanya dengan permasalahan kebahasan adalah dengan kecerdasan dan kemampuan yang dimiliki oleh setiap anak seharusnya diarahkan pada pengembangan pemerolehan bahasa nasional yang baik dan bahasa internasional. Sehingga pendidikan akan melahirkan generasi bangsa yang tidak hanya expert dalam bahasa asing, namun juga menjaga bahasa nasionalnya dengan upaya pemertahanan dan pelestarian. Bahasa Indoensia harus mendapatkan tempat yang equal dengan bahasa internasional didalam kurikulum dan arah kebijakan pengembangan lembaga, bukan justru dikesankan sebagai bahasa yang marginal. Dalam konten kebijakan pendidikan, bahan ajar hingga perangkat sekolah serta guru harus memiliki kesadaran diri untuk mencintai bahasa Indonesia dan membimbing peserta didik untuk juga mempraktikanya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga mampu menciptakan common sense akan kecintaan terhadap warisan budaya luhur bangsa, salah satunya bahasa Indonesia. Jika bukan generasi muda yang peduli dengan budayanya, bukan tidak mungkin Indonesia hanya akan menjadi bangsa dengan melting pot culture yang dibanjiri oleh budaya-budaya asing, karena kegagalanya menjaga lokalitasnya.